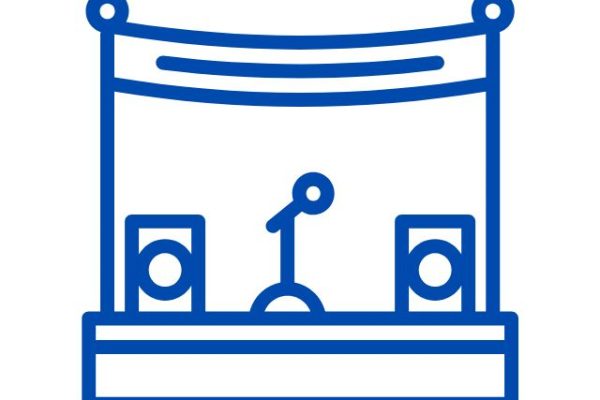Siapa sangka, pesta hajatan di Indonesia seringkali lebih mirip panggung sosial ketimbang sekadar acara keluarga. Bayangkan, ada keluarga yang rela berhutang hanya untuk memastikan acara terlihat “pantas” di mata tetangga. Dari sudut pandang ekonomi murni, keputusan ini jelas tidak masuk akal. Tapi di balik itu ada lapisan norma, gengsi, dan keinginan menjaga citra yang membuat hajatan tetap hidup meski jadi beban finansial.
Hajatan Sebagai Kewajiban Sosial, Bukan Sekadar Perayaan
Kalau ada yang bilang hajatan hanya urusan pribadi, di Indonesia jawabannya jelas: salah besar. Acara pernikahan, khitanan, atau syukuran sudah dianggap kewajiban sosial. Bahkan, kalau sebuah keluarga tidak menggelar hajatan yang meriah, mereka bisa dicap pelit, enggak tahu adat, atau bahkan dianggap belum mapan secara ekonomi. Label semacam ini lebih menakutkan daripada cicilan utang yang menunggu setelah acara selesai.
Tekanan Sosial dan Konformitas dalam Budaya Hajatan
Lucunya, tekanan untuk bikin acara besar bukan hanya datang dari masyarakat luar. Kadang keluarga inti sendiri yang mendesak. Konsep konformitas sosial bekerja halus di sini: ketika satu keluarga bikin pesta meriah, keluarga lain merasa wajib melakukan hal yang sama. Ada yang menyindir terang-terangan, ada juga yang diam-diam bikin malu. Intinya, standar acara “baik” tidak ditentukan keluarga, melainkan masyarakat.
Citra Diri dan Konsep Face Saving di Balik Hajatan
Fenomena hajatan juga erat kaitannya dengan face saving alias menjaga muka. Dalam budaya kolektif seperti Indonesia, harga diri bukan milik individu, tapi ditanggung keluarga besar. Kalau hajatan terlalu sederhana, aib itu bukan hanya menimpa pasangan pengantin, tapi seluruh keluarga. Maka jangan heran, biaya hajatan sering diperlakukan seperti investasi citra sosial—mahal, tapi dianggap layak.
Costly Signaling: Menghabiskan Uang Demi Tampil Berkelas
Dalam ilmu ekonomi ada istilah costly signaling theory. Intinya, orang rela mengeluarkan biaya besar untuk menunjukkan status. Hajatan di Indonesia persis contoh nyata teori ini. Dekorasi mewah, makanan melimpah, hingga ribuan undangan jadi sinyal bahwa keluarga tersebut punya modal sosial dan ekonomi. Meski sebenarnya, tidak sedikit yang hanya membangun “ilusi kemampuan” dengan cara berhutang atau menggadaikan aset.
Modal Budaya: Kenapa Hajatan Dianggap Investasi Sosial
Tidak berhenti di gengsi, hajatan juga dilihat sebagai bentuk modal budaya. Dengan menggelar acara sesuai tradisi, keluarga mendapat pengakuan sosial, menjaga jaringan kekerabatan, dan memperkuat identitas budaya. Dalam struktur masyarakat kolektif, modal budaya ini kadang jauh lebih dihargai daripada uang tunai. Maka wajar bila banyak keluarga merasa lebih untung secara sosial meski rugi secara finansial.
Antara Beban Ekonomi dan Solidaritas Sosial
Jika ditanya, kenapa orang Indonesia tetap menggelar hajatan besar meski harus berhutang? Jawabannya sederhana: karena dalam masyarakat kita, dukungan sosial lebih berharga daripada saldo rekening. Hajatan dianggap cara mempererat silaturahmi, menghapus stigma lama, bahkan mengangkat martabat keluarga di mata orang lain. Meski akhirnya, pesta itu lebih sering meninggalkan beban cicilan ketimbang kenangan manis.
Sampai Kapan Tradisi Hajatan Berjalan dengan Pola Sama?
Hajatan di Indonesia bukan sekadar pesta. Ia adalah pertunjukan simbolik, ajang pembuktian, dan sarana menjaga muka. Tapi pertanyaan yang menggantung adalah: sampai kapan tradisi ini akan terus dipertahankan tanpa mencari bentuk baru yang lebih sederhana namun tetap bermakna? Karena pada akhirnya, martabat keluarga seharusnya tidak diukur dari seberapa megah pestanya, tapi dari bagaimana mereka membangun harmoni sosial yang tulus.