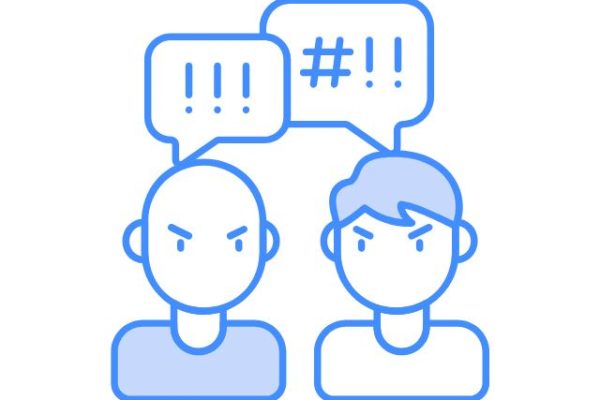Ini cerminan dari gaya hidup gengsian, ilusi status sosial, dan sistem sosial kita yang makin permisif terhadap perilaku egois. Dan ironisnya, makin banyak yang ngelakuin, makin dianggap biasa.
Fenomena ini makin ramai terutama di kawasan padat kelas menengah perkotaan. Di sana, simbol status lebih penting daripada kebutuhan nyata. Mobil jadi ajang pamer. Padahal fungsinya sebagai alat transportasi malah sering ketutup oleh keinginan buat validasi sosial. Yang penting bisa upload foto di feed, pulang kampung naik roda empat, dan dianggap “udah mapan”. Parkir? Dipikir belakangan.
Ketika Pamer Lebih Penting dari Fungsi
Bukan karena butuh, tapi karena takut kalah pamor. Jadi bukannya mikirin cicilan dengan tenang, malah bikin kalkulasi “yang penting keliatan punya dulu”. Ada juga yang berani ambil kredit mepet, meskipun belum tentu bisa urus servis, BBM, apalagi tempat parkir.
Dan gara-gara tekanan sosial itu, banyak yang mikir: “Daripada dikira belum sukses, mending maksa beli.” Padahal ini bukan cuma keputusan finansial, tapi keputusan sosial yang berujung nyusahin tetangga. Mobil nangkring di trotoar, tikungan sempit, bahkan depan rumah orang. Masalah personal jadi beban komunal.
Budaya Ikut-ikutan dan Ilusi Entitlement
Ada istilah dalam psikologi: social proof bias. Ketika satu orang ngelakuin sesuatu dan enggak ditegur, yang lain jadi ngerasa itu sah. “Oh, dia parkir di jalan, berarti boleh dong.” Akhirnya satu dua rumah ikut, lama-lama satu gang. Jalan umum berubah jadi showroom pribadi.
Dan parahnya, ini dibungkus sama mental entitlement illusion. Padahal yang dibayar itu kontribusi warga negara, bukan hak buat nyusahin sesama. Yang lebih miris lagi, orang-orang yang pakai logika “udah biasa kok” justru jadi tembok penghalang perubahan.
Lingkungan yang Gagal Menegur, Negara yang Gagal Mengatur
Ini bukan semata-mata salah individu. Negara dan sistem perkotaan juga punya andil besar. Banyak kawasan pemukiman yang dibangun tanpa pertimbangan ruang parkir. Pemerintah setengah hati dalam penertiban. Teguran cenderung reaktif, bukan preventif. Dan masyarakat makin terbiasa dengan ketidakteraturan.
Krisis ini makin nyata ketika ruang publik jadi korban. Anak-anak kehilangan ruang bermain. Ambulans susah masuk. Sampah enggak bisa diangkut. Semuanya demi mobil yang bahkan enggak punya tempat tidur layak.
Gaya Hidup Gengsi dan Rantai Konsumsi yang Merusak
Beli mobil jadi langkah awal dari maraton ilusi. Habis beli mobil, lanjut interior rumah, gadget mahal, fashion branded. Semua buat tampak sukses. Tapi fondasi keuangan rapuh. Banyak yang hidup dari cicilan ke cicilan. Gaji cuma numpang lewat, stres bertambah, kualitas hidup makin jauh dari kata nyaman.
Dan ketika semua orang berlomba dalam ilusi, tekanan makin kencang. Yang belum punya merasa tertekan buat ikut. Yang udah punya makin nekat buat upgrade. Padahal semua ini bisa dihindari kalau fokusnya digeser dari “apa kata orang” ke “apa yang benar-benar dibutuhin”.
Solusinya? Mulai dari Ngerem Gengsi
Enggak semua orang wajib punya mobil. Kalau belum siap finansial dan fasilitas, lebih baik cari alternatif transportasi yang sesuai. Pemerintah juga mesti tegas soal aturan kepemilikan kendaraan: enggak ada garasi, jangan beli. Edukasi publik soal ruang bersama perlu ditingkatkan. Dan yang paling penting: mulai normalisasi hidup secukupnya, bukan hidup buat pamer.
Enggak perlu malu bilang belum siap. Justru itu langkah pertama buat hidup lebih rasional. Kalau enggak mulai dari sekarang, budaya parkir sembarangan ini akan jadi warisan sosial yang terus merusak kenyamanan bersama.
Mobil itu kendaraan, bukan kredensial. Kalau ruang buat parkir aja enggak ada, berarti ruang buat berpikir juga mungkin belum cukup. Jadi, daripada ikut-ikutan gaya hidup yang dibangun di atas tekanan sosial dan ilusi keberhasilan, lebih baik jadi bagian dari masyarakat yang mikir dua kali sebelum ambil keputusan.