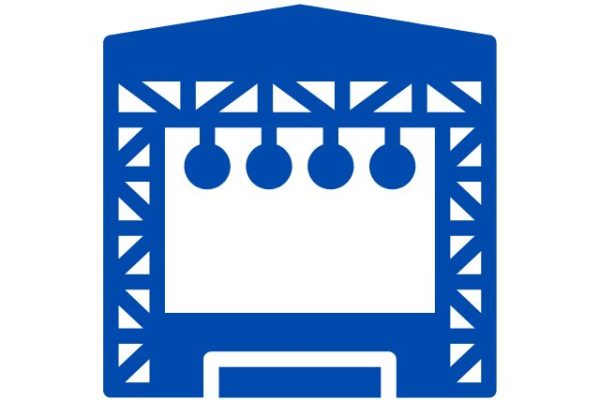Biasanya orang menganggap kematian adalah momen duka yang butuh ruang tenang. Tapi di banyak komunitas Indonesia, kehilangan justru membuka pintu ke babak baru: hajatan kematian. Ada tahlilan, selametan, bahkan acara 1000 harian. Ritual ini seolah wajib dijalankan meskipun keluarga sebenarnya sedang berada di titik terlemah, baik secara mental maupun finansial.
Tekanan Norma dalam Hajatan Kematian
Fenomena biaya besar dalam hajatan kematian muncul bukan karena keluarga ingin pesta, melainkan karena norma. Kalau enggak bikin acara sesuai “standar,” risiko dicap kurang berbakti atau enggak hormat pada almarhum menanti. Norma ini sudah berjalan turun-temurun dan disebut dalam psikologi sosial sebagai normative social influence. Jadi keluarga lebih takut omongan tetangga ketimbang beratnya hutang setelah acara selesai.
Pluralistic Ignorance: Salah Tafsir yang Jadi Tradisi
Lucunya, banyak orang sebenarnya keberatan dengan hajatan kematian yang mahal. Tapi karena mereka mengira orang lain setuju, semua ikut arus. Fenomena ini dikenal sebagai pluralistic ignorance. Jadi, walau mayoritas keluarga ingin sederhana, tekanan sosial membuat mereka tetap menggelar acara besar. Sebuah salah kaprah kolektif yang bikin tradisi berjalan meski banyak pihak menderita.
Identitas Sosial dan Wajah Keluarga
Hajatan kematian bukan sekadar doa, tapi juga simbol identitas sosial keluarga dalam budaya kolektivis. Kalau acara terlihat mewah, keluarga dianggap religius, patuh, dan mapan. Kalau sederhana? Bisa dicap miskin, pelit, atau enggak peduli. Tekanan menjaga wajah sosial inilah yang membuat keluarga berhutang, menjual aset, bahkan mengorbankan pendidikan anak. Semua demi citra sementara yang sebenarnya enggak pernah sempurna di mata orang lain.
Dari Spiritualitas ke Beban Psikologis
Ironisnya, doa yang seharusnya jadi inti justru tertutup logistik acara. Alih-alih mendoakan almarhum dengan khusyuk, keluarga sibuk mikirin kursi, konsumsi, dan hiburan. Hajatan kematian berubah jadi panggung sosial, bukan lagi ruang spiritual. Bahkan rasa bersalah kolektif menambah beban, karena keluarga merasa berdosa kalau acara enggak sesuai ekspektasi masyarakat.
Lingkaran Hutang dan Konsekuensi Jangka Panjang
Di banyak kasus, hajatan kematian jadi pintu masuk hutang berkepanjangan. Keluarga yang baru kehilangan malah jatuh miskin, aset terjual, bahkan masa depan anak ikut dikorbankan. Semua karena tradisi yang dipaksakan demi menjaga reputasi sosial. Ironisnya, setelah acara selesai, komentar miring tetap ada: makanan kurang, tamu enggak puas, atau acaranya dianggap biasa aja.
Saatnya Menggali Makna Ulang
Hajatan kematian seharusnya jadi momen doa, refleksi, dan kebersamaan. Tapi tekanan norma, wajah sosial, serta salah tafsir konsensus membuatnya jadi beban finansial dan psikologis. Selama status sosial dianggap lebih penting daripada kenyamanan keluarga, siklus ini akan terus berulang.
Pertanyaan pentingnya: apakah tradisi ini bisa dijalankan dengan sederhana tanpa kehilangan makna? Kalau doa bisa dilakukan dengan tulus, kenapa harus ditutupi dengan beban hutang?