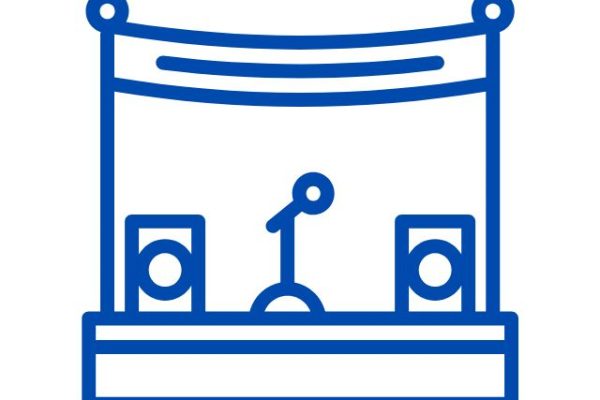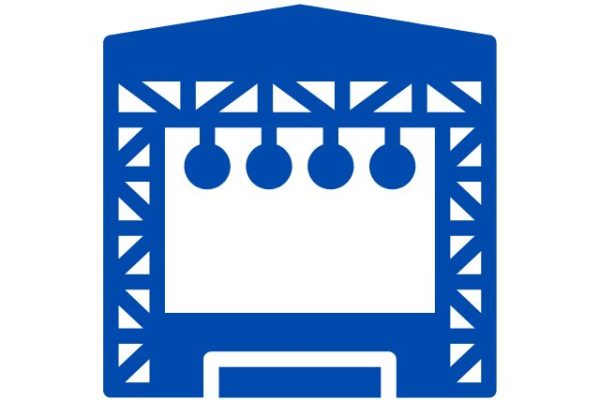Di permukaan, banyak orang mengira perceraian selalu bermula dari hilangnya cinta atau hadirnya orang ketiga. Namun di lapisan masyarakat miskin, alasan terbesar sering kali justru sederhana — uang. Tapi, akar masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar angka di rekening. Ia berhubungan dengan tekanan sosial, perasaan gagal, dan pola pikir yang perlahan menggerogoti fondasi rumah tangga. Fenomena ini ibarat bom waktu yang pelan-pelan menghancurkan hubungan dari dalam, tanpa disadari oleh pasangan yang menjalaninya.
Luka Tak Terlihat di Balik Perbandingan
Ironisnya, banyak pasangan miskin bukan sekadar tertekan karena kekurangan uang, tapi karena terus-menerus merasa lebih buruk dibanding orang lain. Saat tetangga membeli motor baru atau saudara bisa liburan, muncul rasa rendah diri yang sulit dijelaskan. Dalam psikologi sosial, kondisi ini dikenal sebagai relative deprivation — rasa tidak puas karena membandingkan diri dengan standar hidup orang lain.
Dampaknya luar biasa. Suami merasa gagal menafkahi, istri merasa hidupnya kurang beruntung. Pertengkaran pun muncul bukan karena kebutuhan yang tak terpenuhi, melainkan karena luka batin akibat perbandingan yang terus berulang. Media sosial memperparah semuanya. Foto keluarga bahagia, rumah rapi, hingga gaya hidup “sukses” menjadi racun visual yang menumbuhkan rasa iri dan kecewa. Akhirnya, pasangan mulai melihat satu sama lain bukan sebagai teman berjuang, tetapi sebagai simbol kegagalan.
Dari Tagihan Jadi Pertengkaran Emosional
Tekanan ekonomi tidak hanya menghantam dompet, tapi juga emosi. Dalam teori psikologi sosial dikenal istilah stress spillover effect — ketika stres dari satu aspek kehidupan menular ke aspek lainnya. Tagihan listrik yang belum dibayar bisa berujung pada pertengkaran besar karena piring belum dicuci.
Pasangan miskin jarang punya ruang sehat untuk melepaskan tekanan. Terapi tidak terjangkau, hiburan terbatas, dan waktu istirahat pun sering tidak ada. Akibatnya, stres menumpuk tanpa ventilasi. Suami yang lelah bekerja menjadi pendiam atau mudah marah, sementara istri yang frustrasi merasa diabaikan. Komunikasi yang dulunya hangat berubah menjadi ajang tudingan. Perlahan, empati lenyap, digantikan rasa saling curiga.
Ketika Cinta Tak Lagi Cukup
Banyak pasangan memasuki pernikahan dengan keyakinan bahwa cinta mampu menaklukkan segalanya. Namun realitas tidak seindah itu. Cinta yang dulu jadi bahan bakar utama kini terhimpit oleh cicilan, kebutuhan anak, dan harga sembako yang terus naik.
Dalam psikologi sosial, kesenjangan antara harapan dan kenyataan disebut Frustration-Aggression Cycle. Ekspektasi yang gagal berubah menjadi kemarahan. Bukan lagi marah karena kekurangan uang, tapi karena merasa pasangan tidak memenuhi janji bahagia yang dulu diucapkan. “Aku ingin hidup sederhana, tapi bahagia,” berubah menjadi, “kenapa hidup kita begini terus?”
Kekecewaan yang menumpuk ini justru lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Pasangan merasa dikhianati oleh impian yang mereka ciptakan bersama.
Luka Tak Kasat Mata yang Menghantam Harga Diri
Dalam masyarakat, kemiskinan sering kali diiringi dengan label negatif. Suami dianggap gagal, istri dicap tidak becus mengatur rumah tangga. Pandangan ini bukan hanya datang dari orang luar, tapi juga dari keluarga sendiri.
Teori labeling menjelaskan bahwa ketika seseorang terus-menerus dilabeli hal negatif, lama-lama ia mempercayainya. Suami mulai merasa tidak berharga, istri kehilangan rasa percaya diri. Hubungan pun berubah arah: dari saling mendukung menjadi saling menyalahkan.
Banyak pasangan sebenarnya masih saling menyayangi, tetapi tidak tahan hidup di bawah sorotan penilaian sosial. Perceraian kemudian dianggap sebagai cara untuk “menghapus malu”, meskipun bukan solusi sebenarnya.
Ketika Peran Gender Berbalik
Dalam rumah tangga miskin, uang bukan hanya alat bertahan hidup — ia juga menjadi simbol kekuasaan. Ketika suami tidak bisa lagi menafkahi, harga dirinya terguncang. Sebaliknya, ketika istri yang mengambil peran pencari nafkah, dinamika kekuasaan bergeser.
Fenomena ini disebut power dynamic, ketidakseimbangan peran yang memicu konflik tersembunyi. Suami merasa tersisi, istri merasa tidak dihargai. Percakapan sederhana berubah jadi arena pertarungan ego. Dalam situasi keuangan yang serba terbatas, perebutan kendali ini justru makin tajam.
Alih-alih saling melengkapi, pasangan berubah menjadi pesaing dalam satu atap. Ketika keseimbangan sudah hancur, perceraian kerap menjadi pilihan terakhir — bukan karena tidak cinta, tapi karena kehilangan rasa hormat dan kendali.
Ketika Rasa “Tidak Cukup” Menggerogoti Cinta
Hidup miskin sering melahirkan scarcity mindset — pola pikir kelangkaan yang membuat seseorang hanya fokus pada masalah jangka pendek. Pikiran terus dipenuhi kekhawatiran tentang “besok makan apa” atau “bagaimana bayar utang minggu ini.”
Pola pikir ini mematikan kemampuan untuk berpikir jernih. Setiap percakapan jadi pendek, emosional, dan penuh tudingan. Rasa syukur memudar, digantikan oleh rasa kurang yang tidak ada ujungnya. Akhirnya, pasangan berhenti melihat apa yang mereka punya dan hanya fokus pada apa yang tidak dimiliki.
Hubungan kehilangan makna karena cinta dikalahkan oleh rasa takut dan kekhawatiran yang konstan.
Kemiskinan Tidak Hanya Soal Uang, Tapi Soal Luka Kolektif
Perceraian di kalangan miskin tidak bisa dijelaskan dengan satu alasan. Ia adalah hasil akumulasi dari stres finansial, tekanan sosial, ekspektasi yang patah, stigma budaya, dan pola pikir kelangkaan yang menciptakan lingkaran penderitaan.
Masalah ekonomi hanyalah pemicu awal. Yang benar-benar menghancurkan adalah cara kemiskinan mengubah cara orang memandang diri dan pasangannya. Dalam kondisi di mana bertahan hidup saja sudah berat, menjaga cinta tetap utuh menjadi tantangan yang nyaris mustahil.
Pernikahan di bawah tekanan ekonomi ibarat berdiri di atas pasir basah — terlihat stabil dari luar, tapi perlahan tenggelam jika tak segera diselamatkan.