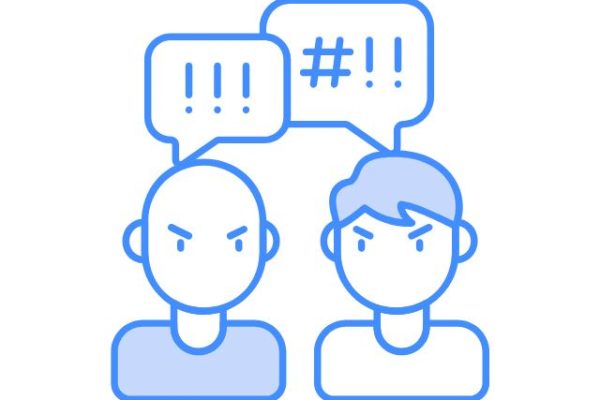Banyak orang datang bukan untuk bersilaturahmi, tetapi untuk bertahan dari tekanan sosial yang tidak terlihat.
Pertanyaan seperti kapan menikah, sudah kerja di mana, kapan punya rumah, hingga berapa gajimu telah bertransformasi menjadi senjata halus yang menekan harga diri seseorang.
Alih-alih saling menguatkan, sebagian keluarga justru menjadikan Lebaran sebagai tempat memastikan siapa yang berada di “atas” dan siapa yang dianggap “tertinggal”.
Budaya Pamer Prestasi Lebaran dan Modal Simbolik Keluarga Besar
Fenomena seseorang datang dengan mobil baru, cerita tentang anak yang kerja di kantor prestisius, atau pamer bisnis yang sedang naik bukanlah sekadar kebetulan.
Dalam psikologi sosial, konsep ini dikenal sebagai modal simbolik ala Pierre Bourdieu: yaitu kebutuhan manusia untuk terlihat sukses di mata orang lain.
Lebaran menjadi momen sempurna untuk memamerkan modal simbolik karena:
- pertemuan besar hanya terjadi setahun sekali,
- ada dorongan budaya kolektif untuk menjaga status sosial,
- dan ada ekspektasi bahwa kesuksesan harus terlihat, bukan hanya dirasakan.
Tidak heran jika sebagian keluarga menjadikan Lebaran sebagai ajang tak resmi untuk menunjukkan siapa yang paling “mapan”.
Tekanan Batin Akibat Standar Sosial yang Dipaksakan dalam Keluarga
Di balik senyum dan baju baru, banyak orang yang sebenarnya datang ke acara keluarga dengan hati waswas. Mereka tahu bahwa momen makan bersama itu sering berakhir menjadi sesi interogasi.
Pertanyaan seperti:
“Kapan menikah?”
“Kerja dimana?”
“Punya rumah?”
bukan lagi sekadar basa-basi, tetapi cerminan standar sosial yang dipaksakan.
Bagi mereka yang belum menikah, yang masih merintis karier, atau yang sedang mencari arah hidup, tatapan penuh kasihan bisa terasa jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata.
Pamer Kesuksesan dan Insecurity Terselubung dalam Kumpul Lebaran
Menariknya, orang yang paling sering mengomentari hidup orang lain biasanya adalah mereka yang paling takut kehilangan statusnya.
Psikologi menjelaskan bahwa seseorang yang benar-benar nyaman dengan pencapaiannya tidak membutuhkan validasi sosial.
Namun di banyak keluarga, justru mereka yang paling vokal berbicara tentang pencapaian pribadi adalah yang paling merasakan kecemasannya sendiri.
Pamer menjadi cara menutupi rasa tidak aman, meskipun hasil akhirnya justru membuat orang lain semakin menjauh.
Kenapa Kumpul Keluarga Lebaran Berubah Menjadi Ajang Kompetisi?
Jika dilihat dari luar, seharusnya Lebaran adalah ruang untuk memaafkan, berbagi cerita, dan mempererat hubungan.
Namun dalam praktiknya, banyak keluarga justru membawa standar sosial yang terlalu sempit: harus menikah di usia tertentu, bekerja di tempat “terkenal”, punya rumah sendiri, dan hidup sesuai jalur yang dianggap ideal.
Standar ini diwariskan turun-temurun, sehingga tanpa disadari, banyak orang menjalankan pola yang sama: menilai hidup orang lain berdasarkan jalur hidup mereka pribadi.
False Consensus Effect dalam Dinamika Lebaran Keluarga Besar
Fenomena mempertanyakan hidup orang lain dijelaskan oleh bias kognitif bernama false consensus effect, yaitu keyakinan bahwa cara hidup pribadi adalah cara hidup terbaik dan paling masuk akal.
Maka ketika ada sepupu yang memilih jalur berbeda—misalnya tidak menikah dulu, bekerja di bidang yang tidak mainstream, atau hidup mandiri—mereka dianggap aneh atau salah.
Padahal mereka hanya menjalani hidup sesuai nilai dan kesempatan yang dimiliki.
Dalam masyarakat kolektif seperti Indonesia, bias ini semakin kuat karena budaya menekankan keseragaman, bukan perbedaan.
Pratfall Effect dan Fenomena Orang Terlihat Sempurna tapi Tidak Disukai
Tipe orang yang terlalu sering pamer—gaji, bisnis, jabatan, atau keberhasilan anak—umumnya percaya bahwa mereka sedang membangun citra positif.
Padahal dalam psikologi sosial, Pratfall Effect menunjukkan hal sebaliknya: semakin seseorang terlihat sempurna, semakin besar peluang ia dianggap menyebalkan.
Orang lebih menyukai individu yang manusiawi, yang punya kekurangan, yang tidak memamerkan dirinya berlebihan.
Karenanya, orang yang rendah hati justru lebih dihormati daripada yang terlalu menonjolkan pencapaian.
Hierarki Keluarga dan Power Distance dalam Acara Lebaran
Di banyak keluarga Indonesia, mereka yang lebih tua atau dianggap lebih sukses sering merasa punya hak untuk menilai hidup orang lain.
Komentar seperti:
“Kerja di situ masa gajinya segitu?”
“Kamu sudah umur segini kok belum menikah?”
“Sudah waktunya rumah sendiri, jangan ngontrak terus.”
bukan hanya opini, tetapi bentuk hierarki yang tidak sehat.
Konsep power distance menjelaskan bahwa dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, suara orang muda atau yang dianggap belum “berhasil” sulit dihargai.
Akibatnya, mereka memilih diam meski merasa terluka.
Mengapa Banyak Orang Menghindari Kumpul Keluarga Lebaran?
Banyak orang mulai memilih tidak hadir dalam acara keluarga besar bukan karena tidak menghormati tradisi, tetapi karena lelah menghadapi kompetisi tidak terlihat.
Tekanan untuk tampil sempurna, menjaga citra, dan menjawab pertanyaan yang menghakimi membuat suasana Lebaran terasa lebih seperti ujian daripada kehangatan.
Mengembalikan Makna Lebaran sebagai Momen Kebersamaan, Bukan Pamer Status
Lebaran seharusnya menjadi ruang untuk saling menguatkan, bukan membandingkan. Keluarga adalah tempat pulang, bukan arena kompetisi. Setiap orang memiliki jalur hidup, ritme, kesempatan, dan tujuan masing-masing.
Mengembalikan makna silaturahmi berarti menghargai keberagaman perjalanan hidup, menahan komentar yang tidak perlu, dan memahami bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dengan standar seragam.
Jika digunakan dengan empati, Lebaran bisa kembali menjadi momen penuh kehangatan. Namun jika tetap dijadikan panggung status dan hierarki, maka banyak orang akan terus merasa bahwa rumah sendiri adalah tempat paling menekan.